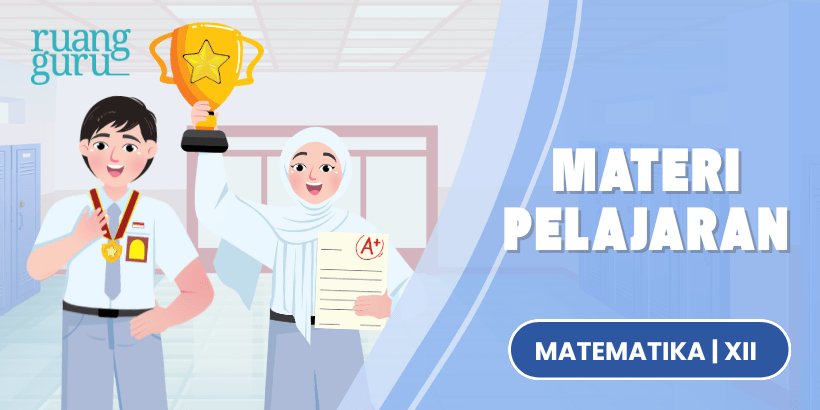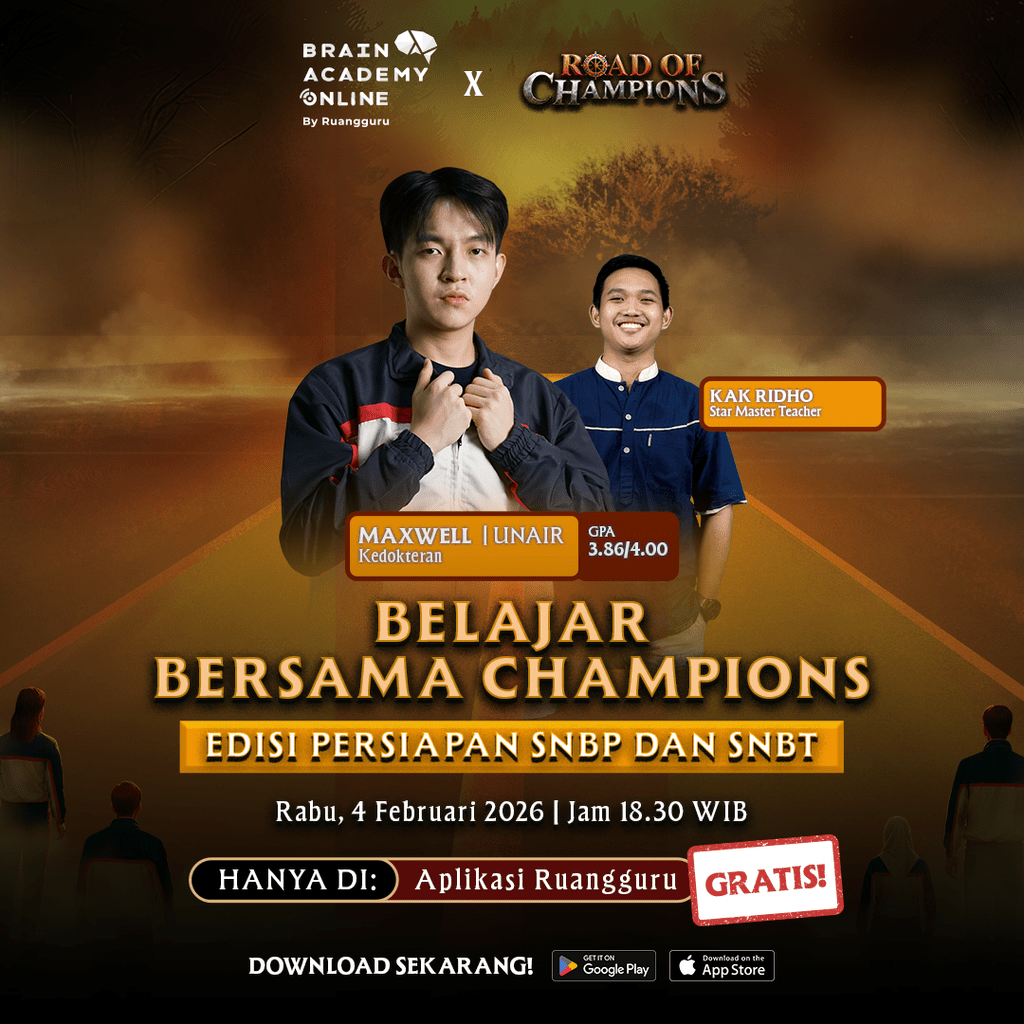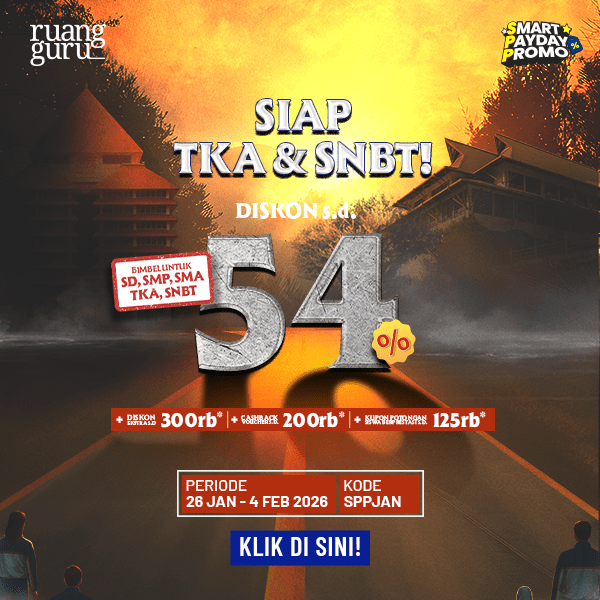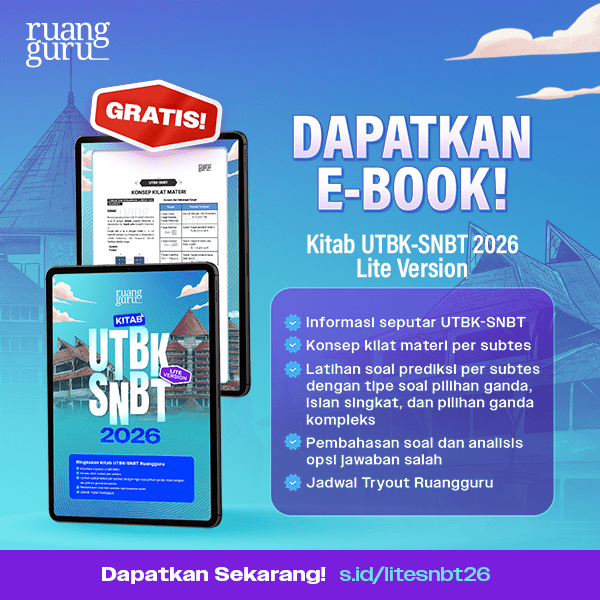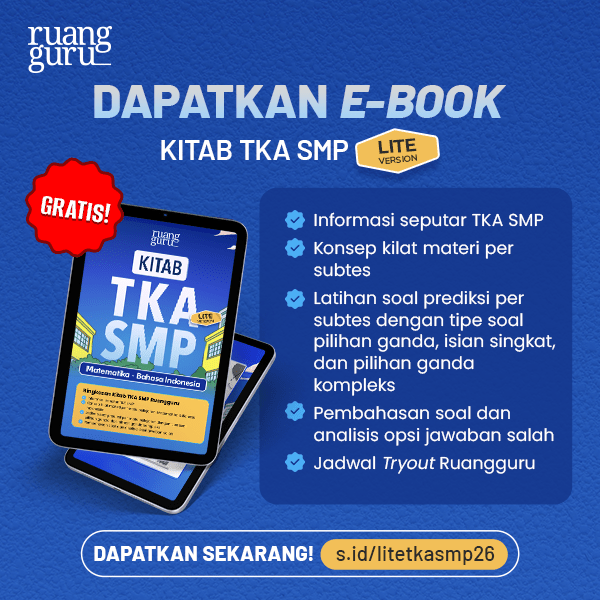Toxic Positivity, Ketika Ucapan Positif Berdampak Negatif

Artikel ini membahas tentang toxic positivity. Bagaimana ternyata kata-kata positif justru dapat berdampak negatif bagi sebagian orang.
—
Sobat Ambyar dan Didi Kempot adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dalam setiap konsernya, Lord of Broken Heart selalu mengajak penontonnya untuk melepas beban.
Lagu-lagunya adalah medium bagi siapa saja, tanpa pandang bulu, untuk menumpahkan kegundahan yang selama ini kita bawa. Dalam sebuah video yang beredar, di konser Didi ada satu laki-laki yang meneriakkan lirik Kalung Emas sambil menangis meronta-ronta. Sementara penonton lain bersorak “Nangiske! Nangiske!” maksudnya, “Nangisin aja! Nangisin aja!”
Didi Kempot adalah musisi campursari yang telah mengeluarkan 800 lagu. Bagi Didi, tidak ada yang salah dengan melepaskan kesedihan. Bagi Sobat Ambyar, tidak ada yang salah dengan menangis di tengah keramaian.
Kita tidak perlu terus-terusan menjadi manusia yang kuat dan bahagia. Kita perlu sadar bahwa sebagai manusia, emosi lain seperti marah dan sedih dan takut itu ada dan tidak apa-apa. Meski begitu, kita harus kuat. Opo wae sing dadi masalahmu, kuwat ora kuwat kowe kudu kuwat. Tapi misale kowe uwis ora kuwat tenan, yo kudu kuwat, candanya dalam akun X (dulu Twitter).
Beberapa di antara kamu mungkin beranggapan bahwa “laki-laki itu harus kuat”. Beberapa di antara kamu mungkin pernah curhat tentang masalahmu ke orang lain, tapi dia menanggapinya dengan, “Ah, gitu doang mah masih mending. Gue pernah lebih parah…” dia kemudian menyuruhmu mengambil hikmahnya dan jangan menyerah dan bersyukur karena di luar sana ada yang hidupnya lebih menyedihkan darimu.
Padahal, bisa jadi kalimat darinya merupakan toxic positivity.
Apa itu Toxic Positivity?
Toxic positivity adalah istilah yang merujuk pada situasi ketika seseorang “memaksa” orang lain untuk merasakan sisi baik dari suatu hal, tanpa memberi kesempatan orang itu untuk meluapkan perasaannya.
Padahal, berdasarkan Psychology Today, menghindari emosi di dalam diri bisa membuat kita kehilangan informasi yang bernilai. Ketika takut, misalnya. Emosimu sebenarnya sedang memberitahu “Hati-hati, ada bahaya di sekitar!” sehingga kamu bisa lebih waspada. Emosi sejatinya adalah informasi; mereka memberimu cuplikan-cuplikan tentang apa yang terjadi di suatu waktu, tapi mereka tidak memberitahu secara pasti apa yang harus kamu lakukan.
Dr. Jiemi Ardian, residen psikiatri di Rumah Sakit Muwardi Solo, memberitahu perbedaan antara toxic positivity dan empati. Jiemi mencontohkan kalimat yang menunjukkan empati. Seperti, “Wajar jika kita merasa kecewa dalam hal ini”, dan “Aku pikir kamu pasti merasa berat saat ini, ya…”
Kalimat-kalimat ini tidak memaksa si penerima untuk mengabaikan emosi negatifnya. Faktanya, tidak semua orang curhat untuk menyelesaikan masalah. Beberapa orang curhat hanya untuk didengar. Orang-orang ini hanya membutuhkan validasi. Dalam Psych Alive, validasi adalah perbuatan untuk memberitahu seseorang bahwa apa yang ia rasakan dan alami itu nyata. Ketika perasaan seseorang tervalidasi dengan didengarkan, ia akan merasa dipahami.
Dan udah, gitu doang cukup. Meskipun masalahnya tidak selesai, orang ini akan merasa lega karena perasaannya terluapkan.

Dalam jurnal Psychological Science, Wood dkk menulis bahwa ketika seseorang terus bilang ke diri sendiri “aku gakpapa”, “aku happy”, “aku kuat” atau kalimat yang berlawanan dengan perasaannya, ini malah semakin menenggelamkan orang tersebut ke perasaan buruk yang makin dalam.
Ironisnya, buku-buku dan seminar motivasi selalu menggaungkan kalimat positif seperti ini. Seakan-akan kita tidak boleh merasakan emosi yang lain. Sewaktu kecil, orangtua juga suka melakukan kesalahan-kesalahan ini. Seolah-olah menangis adalah cara yang salah dalam melampiaskan perasaan. Kita terus diminta memendam perasaan selain bahagia.
Baca Juga: Berbagai Macam Sesat Pikir (Logical Fallacy) yang Harus Kamu Hindari
Coba bayangkan ini. Perasaanmu adalah pompa. Lalu, kamu menahan ujung pompa itu dengan balon. Mungkin untuk sementara waktu tidak apa-apa. Tapi lama-kelamaan, perasaan yang tertahan akan membuat balonnya semakin besar dan pecah.
Kalau itu yang terjadi, akibatnya bisa gawat.
Dalam suatu kasus, kalimat “fake it until you make it” justru menjadi beban. Mette Böll, seorang peneliti asal Denmark pernah melakukan eksperimen. Ia menghadapkan karyawan minimarket pada sebuah situasi sulit. Hasilnya, Böll menemukan bahwa kondisi paling stres bagi karyawan bukanlah berhadapan dengan pelanggan yang menyebalkan, tapi bagaimana ia harus berpura-pura terus positif di depan pelanggannya.
Cara Menghindari Toxic Positivity
Kalau kamu ingat pandemi beberapa tahun silam yang memaksa kamu untuk tidak pergi dari rumah, secara gak langsung kita jadi semakin rentan dengan stres. Tidak bisa dimungkiri, karantina berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Bukan tidak mungkin salah satu dari kita merasa sedih atau bosan atau lelah dengan situasi ini. Bahkan anak perempuan di Probolinggo sampai menangis dan mendatangi sekolahnya karena kangen.
Maka, belajar dari Didi Kempot, lampiaskan saja. Tidak ada yang salah dengan menangis dan bersedih. Putar lagu galau favoritmu, pasang earphone, keraskan volume, dan luapkan emosimu. Terkadang orang lupa bahwa menangis bukan tanda lemah. Air mata justru diciptakan untuk mengingatkan kita bahwa manusia lebih unggul dari sekadar robot.
—
Buat kamu yang dipercaya sebagai teman curhat, belajarlah dari Didi Kempot. Hilangkan toxic positivity. Beri dia tempat untuk meneriakkan perasaannya. Biarkan ia jujur terhadap dirinya sendiri. Kamu mungkin satu-satunya orang yang dipercaya untuk menceritakan masalahnya. Ajak ia menari dengan ambyar. Atau kata Didi Kempot dalam interview-nya di salah satu channel Youtube: “Terima saja. Perasaan itu adalah anugerah.”
Tapi, buat kamu yang mau belajar lebih dalam, yuk cek aplikasi ruangbelajar! Kamu akan belajar dengan seru ditemani Master Teacher yang keren banget!