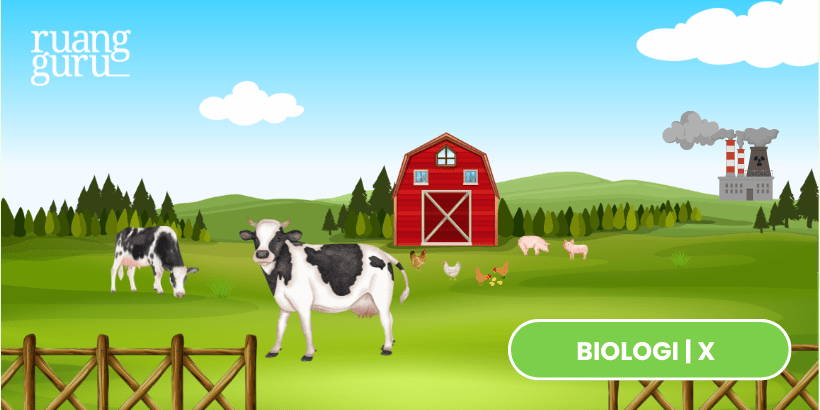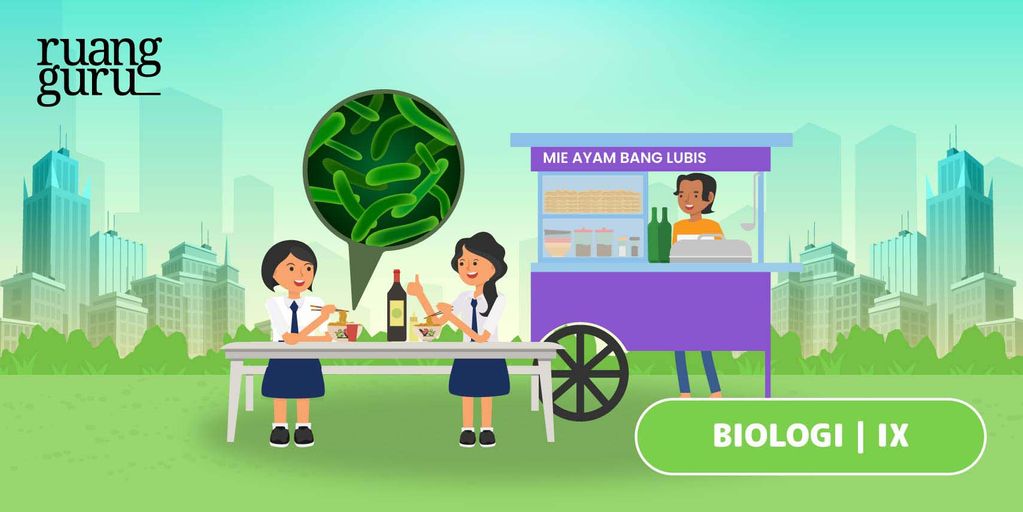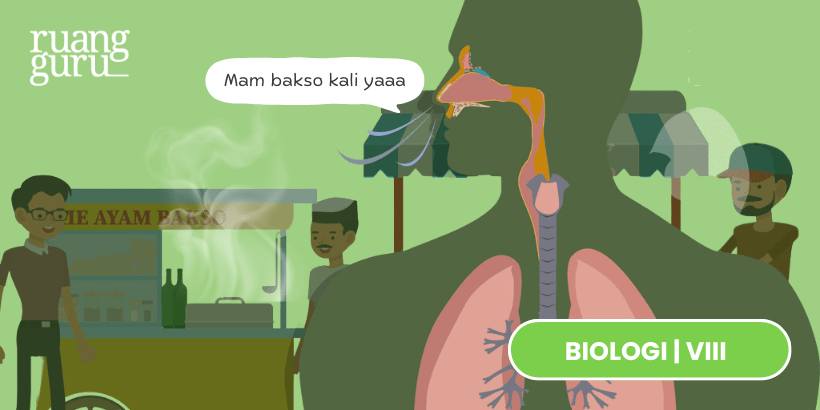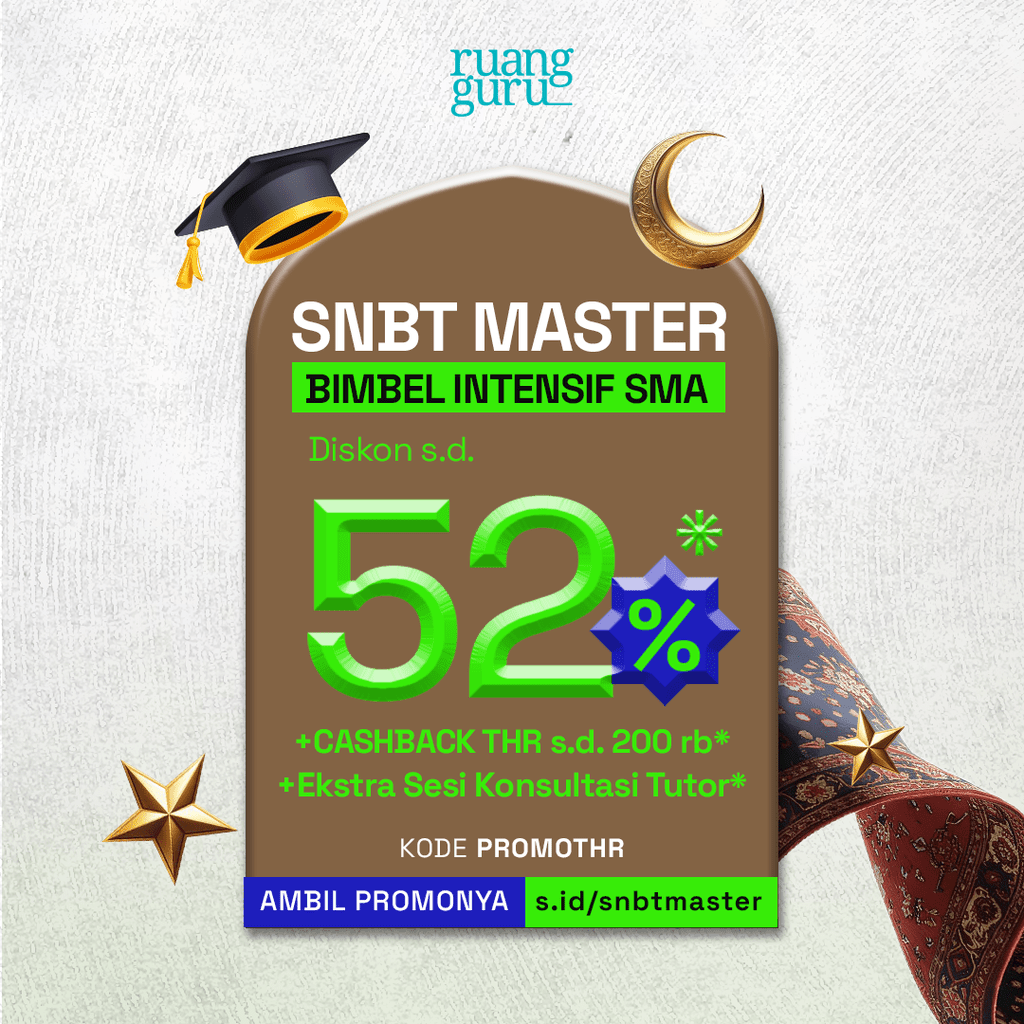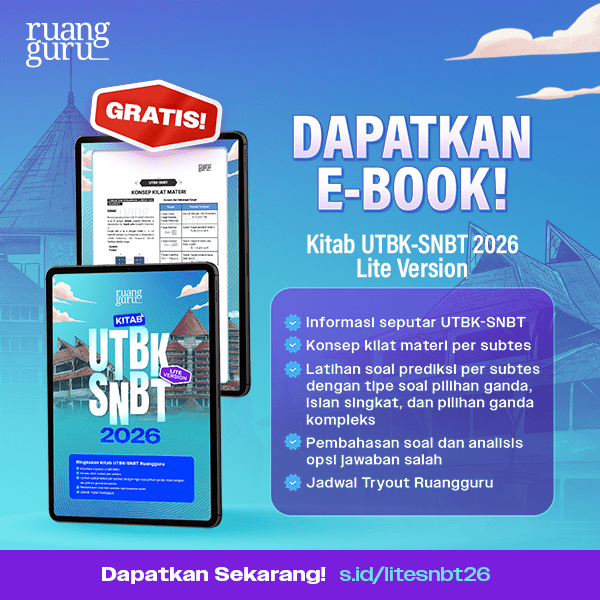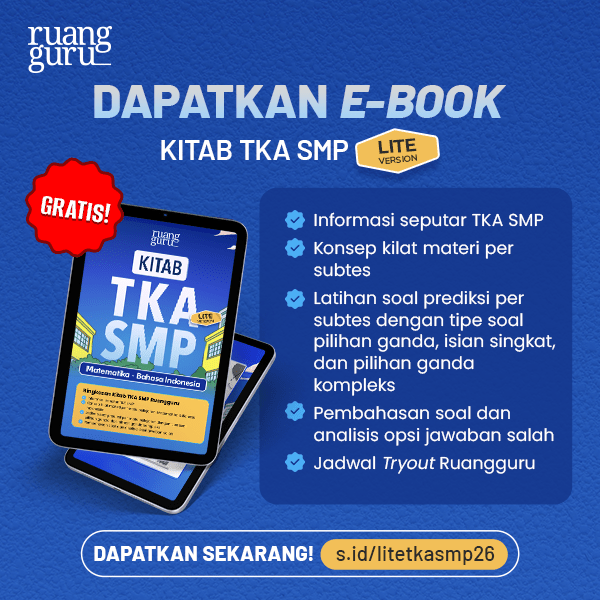Mengenal Emotional Neglect and Suppression dari film NKCTHI

Artikel ini membahas mengenai emotional neglect dan emotional suppression.
—
Awal tahun 2020, anak muda Indonesia tengah ramai membicarakan sebuah film. Obrolan mereka tentang film ini begitu emosional, bahkan banyak yang berkata, “Tonton bareng sama keluarga, biar lebih kerasa.” Banyak dari mereka merasakan alur cerita film ini mirip dengan kehidupan asli mereka.
Film yang berjudul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini menceritakan sepasang suami istri yang mengalami musibah. Sebagai kepala keluarga dengan tiga anak, sang Ayah berusaha dengan segenap hati menjaga keutuhan keluarganya dengan tidak menceritakan musibah tersebut kepada anak-anaknya. Ia menguatkan istrinya agar anak-anaknya dapat hidup dengan bahagia.
Sang Ayah berjuang dengan mengabaikan dan memendam perasaan sedih akibat musibah yang dialami keluarganya. Namun mirisnya, hal tersebut membuahkan hasil yang berkebalikan dengan niat awalnya.
Sebenarnya tidak ada yang salah dengan niat karakter Ayah. Sebagai orang tua yang telah mengalami berbagai macam hal, tentu saja tidak menginginkan anak kita merasakan hal-hal yang membuat mereka terpuruk. Hal itu semata-mata karena kita mengetahui betapa melelahkannya menghadapi masalah yang berat.
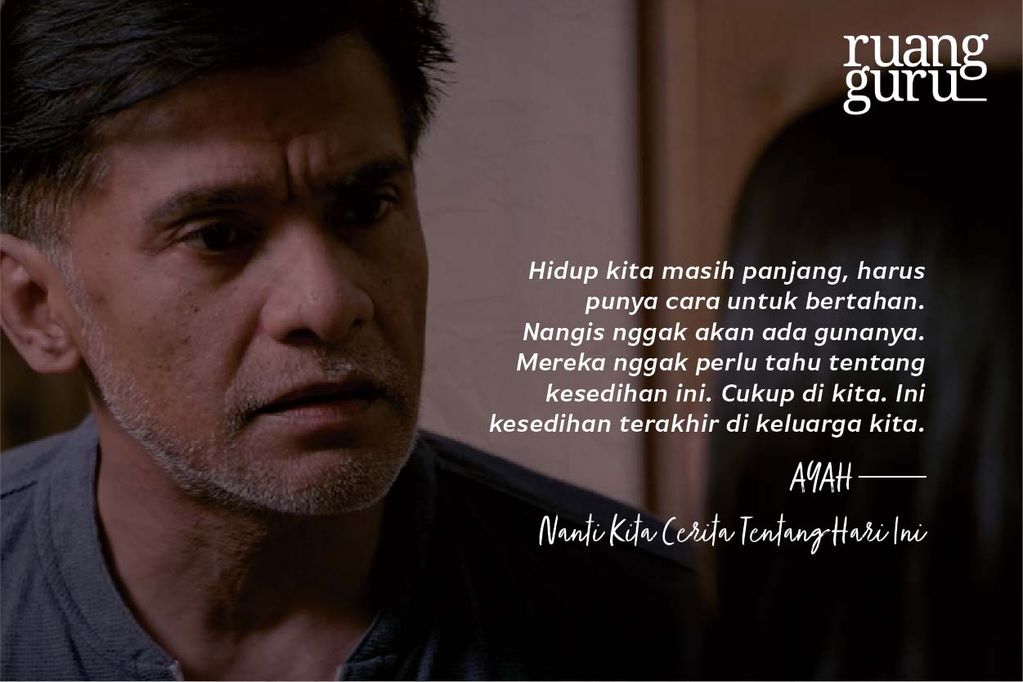 Ayah – NKCTHI (Sumber: Visinema Pictures)
Ayah – NKCTHI (Sumber: Visinema Pictures)
Seperti karakter Ayah pada film NKCTHI, banyak dari kita meyakini, bahwa emosi negatif seperti sedih, marah atau takut, tidak akan ada gunanya, tidak akan membuat situasi buruk menjadi lebih baik. Kemudian hal itu memengaruhi perlakuan kita terhadap anak kita.
Seperti saat anak kita masih kecil dulu. Misalnya, mereka memiliki teman main tetangga. Suatu ketika, tetangga itu pindah rumah, dan anak kita menangis karenanya. Kita dengan sigap mengalihkan perhatian mereka, mungkin dengan memberikannya mainan atau mengajaknya jalan-jalan, agar tidak menangis lagi.
Jika dilihat dari jauh, niat kita memanglah baik dan wajar. Kita menginginkan anak kita tetap bahagia meskipun teman mainnya pergi. Sayangnya, kita tidak tahu apakah perlakuan kita cukup tepat atau tidak.
Saat anak kita menangis, sebenarnya mereka sedang mengenali perasaan yang sedang dialami, “Perasaan apa ini? Kenapa aku menangis ketika teman mainku pergi?” Tiba-tiba kita mengganggu proses itu dengan menghibur mereka, dengan membuat mereka mengabaikan perasaan yang sedang diprosesnya. Lalu anak mulai berpikir, “Oh.. jadi aku tidak boleh merasa seperti ini? Perasaan ini tidak boleh aku rasakan.”
Anak kita kemudian mulai berhenti menangis dan perlahan-lahan terhibur. Namun yang sebenarnya terjadi, hal ini tidaklah baik. Menurut hasil diskusi di sekolah Waldorf, dengan menyangkal atau menganggap emosi negatif yang sedang dirasakan oleh anak itu buruk, akan menyimpulkan bahwa memiliki emosi negatif itu sesuatu hal yang tidak baik. Karena manusia merasakannya setiap hari, maka anak akan beranggapan bahwa mereka salah jika sedang merasakan emosi itu.
Sayangnya, ketika anak sudah berpikir demikian, lama-lama mereka cenderung akan memiliki sifat tidak percaya diri, sering mengkritik diri sendiri, juga kecemasan. Dengan mengabaikan perasaan, dapat membuat anak berpikir bahwa apa yang dirasakannya tidaklah penting. Seiring bertambah usia, mereka akan berhenti mencari perlindungan dan berhenti menceritakan perasaan mereka.
 Aurora – NKCTHI (Sumber: Visinema Pictures)
Aurora – NKCTHI (Sumber: Visinema Pictures)
Perlakuan menganggap emosi negatif tidak penting untuk dirasakan dan cenderung dihindarkan disebut dengan emotional neglect atau pengabaian emosi. Menurut berbagai penelitian, dampak yang dihasilkan oleh pengabaian emosi dipercaya buruk, mulai dari apatis bahkan sampai depresi.
Dampak buruk lainnya, pengabaian emosi membuat anak kita memendam emosi. Misalnya, saat mereka menginjak usia remaja, salah seorang sahabat mereka meninggal. Anak kita tidak menunjukkan tanda-tanda kesedihan, hanya diam seribu kata. Mereka memilih untuk tidak sedih, karena mereka berpikir menangis tidak akan membuat sahabatnya hidup kembali.
Suatu waktu, anak kita sedang minum air putih. Tanpa sengaja, mereka menjatuhkan gelasnya sehingga pecah. Tanpa diduga-duga, mereka menangis sejadi-jadinya. Bisa jadi, saat itu yang dipikirkan mereka adalah, “Jagain gelas biar nggak pecah aja aku nggak bisa. Apalagi jagain sahabat.”
Kemudian mereka merasa bersalah dalam waktu yang sangat lama. Atau yang lebih buruk anak kita hanya diam, dan memendam perasaan sedih mereka hingga terlalu banyak, sampai-sampai mereka merasa hampa. Perlakuan ini disebut sebagai emotional suppression.
Dalam kasus lain, suatu saat di kantor, kita ditegur oleh atasan di depan banyak orang, padahal pekerjaan yang kita lakukan sudah benar. Namun, karena kita takut dengan atasan, kita menahan amarah dan tetap profesional. Kemudian saat pulang ke rumah, tiba-tiba anak kita mengejutkan kita dengan melompat dari balik pintu. Kita langsung membentaknya dan memarahinya. Padahal saat itu mereka hanya ingin bermain.
Memendam emosi tidak hanya berdampak buruk bagi kita. Bahkan orang yang tidak salah sama sekali bisa menjadi korban. Seperti kasus yang sudah disebutkan sebelumnya. Kita memendam amarah kita, lalu meledakkannya kepada anak kita. Jika dilihat, memendam emosi hanya berpengaruh pada kondisi mental. Tapi ternyata kita tidak menyadari, bahwa memendam emosi akan berpengaruh pada fisik juga.
Penelitian dari Harvard School of Public Health and the University of Rochester menyebutkan bahwa, orang yang memendam perasaannya, dapat meningkatkan risiko kematian dini sebesar 30% dengan risiko didiagnosis mengidap kanker sebesar 70%.
Betapa mengerikannya dampak dari pengabaian dan pemendaman emosi ini. Padahal sedari awal, kita hanya menginginkan anak-anak kita dapat hidup tanpa banyak memikirkan masalah. Namun, terkadang kita lupa, bahwa kita sering memikirkan keinginan kita terhadap anak-anak dan melupakan apa keinginan mereka sebenarnya.
Kita lupa bertanya, “Kenapa nangis, nak?” “Sayang, kenapa kamu takut?” Atau “Apa yang membuatmu marah, nak?” Tapi langsung memotong mereka dengan, “Nggak perlu ada yang ditangisi. Kamu nggak boleh cengeng.” “Anak laki-laki harusnya berani.” “Sayang kan cantik, masa marah-marah?”
Kita lupa, bahwa sebenarnya anak kita tidak menginginkan pengabaian perasaan, melainkan penerimaan.
Baca juga: Toxic Positivity: Ketika Ucapan Positif Berdampak Negatif
Jadi, apa yang harus dilakukan?
Sebagai orang tua, hal yang paling sering harus kita lakukan adalah ambil napas dengan tenang, lalu berusaha mengingat kejadian-kejadian yang sudah kita alami.
Smart parents, ingatkah ketika kita mengalami emosi negatif kita malah merasa diuntungkan? Misalnya, suatu ketika kita marah kepada teman kita, yang dengan tidak sadar, mengajak kita melakukan tindakan di luar norma, lalu kita memberikan penegasan bahwa kita tidak akan ikut-ikutan.
Atau, misalnya ketika kita memiliki suatu impian, kita takut tidak berhasil mencapainya karena kemampuan kita. Lalu, kita berusaha menenangkan diri, kemudian merancang strategi untuk mimpi tersebut agar berhasil dicapai.
Ternyata, emosi ini memang menguntungkan bagi kita. Karena sejatinya, emosi yang terkendali dapat memberikan dampak yang baik.
Amarah misalnya, dapat membuat kita lebih tegas dalam membuat keputusan juga memberitahu kita untuk melindungi diri dan melawan ketika kita sedang dalam keadaan yang tidak sesuai dengan prinsip kita.
Ketakutan yang terkendali memberitahu kita untuk berhati-hati dalam bertindak dan memikirkan risiko dari setiap perbuatan. Dalam keadaan tertentu, rasa takut mengingatkan kita bahwa terdapat hal berbahaya untuk kita hindari.
Lalu kesedihan yang terkendali, membuat siklus menjadi lebih lengkap; ketika mengalami musibah, kita dapat berkabung dan melanjutkan hidup tanpa dibayang-bayangi oleh masa lalu. Karena rasa sedih memberitahu kita untuk menenangkan diri dan tidak terburu-buru untuk menyembuhkan diri.
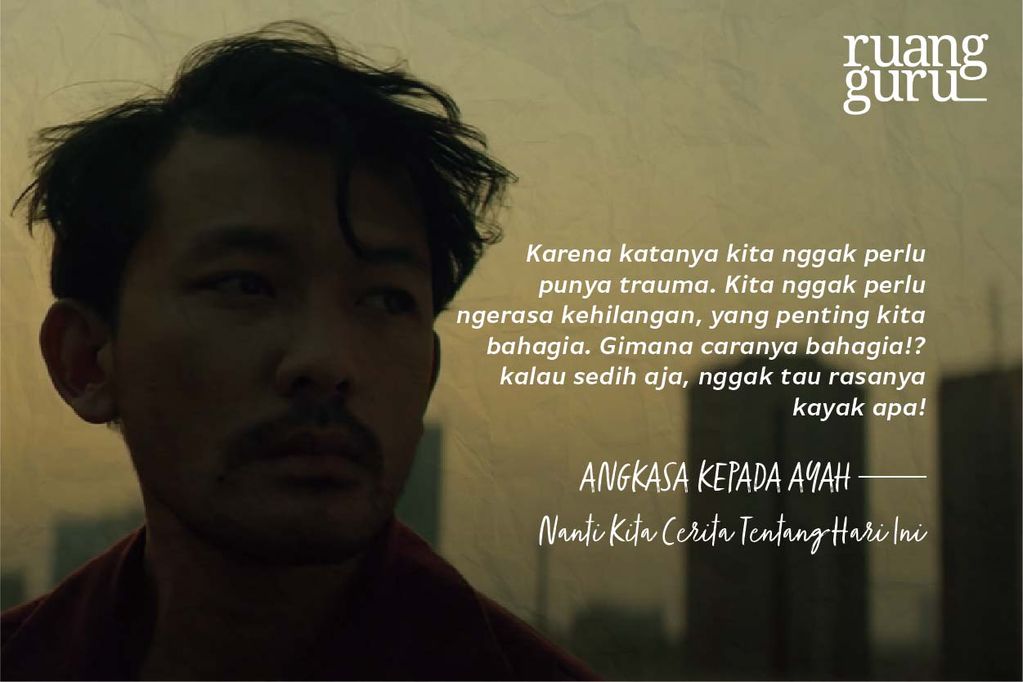 Angkasa – NKCTHI (Sumber: Visinema Pictures)
Angkasa – NKCTHI (Sumber: Visinema Pictures)
Membiarkan kita merasakan seluruh emosi, baik itu positif ataupun negatif, adalah hal yang normal. Merasa sedih, marah, takut, senang, sejatinya membedakan apa yang disebut dengan manusia dan robot.
Tentunya, setiap orang tua menginginkan anaknya untuk hidup sebagai manusia yang utuh dan dengan membantu anak merasakan emosi ini akan sangat membantu mereka. Tammy Betzko, seorang guru sekolah Waldorf, menyebutkan beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk anak kita mengenai hal ini.
Tammy berpendapat bahwa kita hanya perlu bernapas dan tenang, lalu membiarkan anak melampiaskan emosinya. Menurutnya, kita tidak perlu berbicara banyak hal. Cukup dengan menyampaikan “Bunda di sini, nak. Nggak apa-apa kamu merasakan apa yang sedang kamu rasakan.” Karena, hal terpenting bagi orang tua adalah menjadi tempat yang nyaman, menerima dan tidak menghakimi.
Selanjutnya, kita juga bisa membantu anak dengan menyebutkan apa yang sedang mereka rasakan, “Sepertinya adik lagi marah/sedih/takut.” Hal ini dapat menumbuhkan kesadaran diri dan kecerdasan emosi.
Selain itu, ketika kita sedang berhadapan dengan mereka yang sedang meluapkan emosinya, kita dapat memberikan peraturan dasar agar mereka dapat belajar mengendalikan perasaannya.
Misalnya ketika anak marah, kita bisa memberi tahu mereka, “Adik boleh marah, tapi jangan melukai adik sendiri atau ayah dan bunda atau juga orang lain. Adik juga tidak boleh merusak barang yang tidak boleh dirusak. Tapi adik boleh marah.” Setiap anak berbeda-beda ketika mengekspresikan marah, ada yang merobek kertas, ada yang berteriak, ada yang menginjak-injak bumi dan lain-lain.
Saat anak mengekspresikan emosinya, kita ternyata cukup dengan hadir di hadapan mereka dan memfasilitasi (membantu mengekspresikan) perasaannya. Setelah itu, biarkanlah mereka, dan terkadang, kebijaksanaan anak sendiri akan menjadi panduan yang terbaik. Jika memang kita perlu melakukan sesuatu, kita dapat menunggu sampai mereka selesai mengekspresikan emosi mereka.
Semakin anak terlatih dengan mengekspresikan emosinya, anak cenderung tidak akan memendam perasaannya lagi, dan menjadi terbuka dengan kita. Hal ini pertanda baik. Kedekatan antara orang tua dengan anak akan erat, karena kita sudah menjadi tempat yang aman dan terpercaya baginya untuk berekspresi.
Tidak dapat dipungkiri, melihat anak menangis karena sedih, marah atau ketakutan itu sulit. Membayangkan bagaimana mereka sulit menghadapi situasi yang mengharuskan mereka beremosi adalah hal yang berat. Karena kita sudah pernah merasakannya dan hal itu sangat melelahkan untuk dilalui.
Tapi sebagai orang tua, kita harus ingat kembali, bahwa sejatinya dengan membantu anak merasakan emosi, sama halnya dengan membantu mereka menjadi manusia yang berperasaan.
Referensi:
Bailey, Paola, ‘Childhood emotional neglect; how to replenish what wasn’t there (part 2)’, 23 Maret 2019 [online]. Available at: https://blog.paolabailey.com/childhood-emotional-neglect-how-to-replenish-what-wasnt-there-part-2 (Accessed: 15 September 2020)
C.E, Lucy, ‘Are there downsides to always trying to be positive?’, Health Agenda, Februari 2018 [online]. Available at : https://www.hcf.com.au/health-agenda/body-mind/mental-health/downsides-to-always-being-positive (Accessed: 15 September 2020)
Parvez, Hanan. ‘Emotional suppression: Causes and cpnsequences’, PsychMechanics, 27 Agustus 2014 [online]. Available at: https://www.psychmechanics.com/effects-of-suppressing-your-emotions/ (Accessed: 15 September 2020)
Raypole, Crystal. ‘Let It Out: Dealing With Repressed Emotions‘, Healthline, 31 Maret 2020 [online]. Available at: https://www.healthline.com/health/repressed-emotions (Accessed: 15 September 2020)
Waldorf. ‘How do we support big emotions in our children?’, Waldorf School of BEND [online]. Available at: https://www.bendwaldorf.com/how-do-we-support-big-emotions-in-our-children/ (Accessed: 15 September 2020)